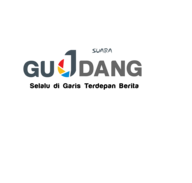Oleh: Rahman Syamsuddin
(Dosen Hukum, Direktur literasi hukum indonesia dan Pemerhati Kebijakan Fiskal)
Kondisi perekonomian nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak sektor industri mengalami penurunan permintaan, tekanan biaya operasional meningkat, dan dunia usaha menghadapi tantangan likuiditas yang serius.
Dalam situasi seperti ini, justru muncul problematika yang kerap luput dari perhatian: pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memberatkan dunia usaha, terutama mereka yang tengah merosot secara keuangan atau bahkan sudah dalam tahap pailit.
PPN, sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara, idealnya menjadi alat fiskal yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan responsif terhadap kondisi ekonomi riil.
Namun dalam praktik, justru PPN menjadi beban tambahan yang rumit secara administratif dan menyulitkan dari sisi waktu pemungutannya.
Salah satu kasus nyata yang terjadi di lapangan adalah pada perusahaan-perusahaan yang terpaksa melepas aset mereka melalui mekanisme lelang oleh Kantor Lelang Negara.
Proses ini sering kali dilakukan dalam konteks likuidasi atau kepailitan. Ironisnya, setelah aset dilelang dan dana hasil penjualan dibagikan kepada kreditur dan negara, perusahaan tiba-tiba menerima tagihan PPN atas aset tersebut, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut masih berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Padahal, dari perspektif pengusaha, semua kewajiban sudah dianggap selesai begitu lelang dinyatakan tuntas oleh negara.
Bahkan, dalam banyak kasus, perusahaan tidak lagi memiliki dana untuk membayar tagihan tambahan tersebut. Lalu, bagaimana mungkin pajak dipungut setelah transaksi selesai, dan kepada siapa beban ini harus ditagihkan jika perusahaan sudah tidak lagi aktif?
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: